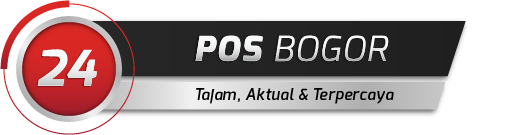“The elephants created this jungle,” kata narasi dalam film Jungle Book, sesaat setelah Bagheera sang lodaya meminta Mowgli menunjukkan penghormatan kepada serombongan gajah yang melintas. Gajah-gajah itulah yang membentuk hutan. Mereka mengerti seluk-beluknya.
Konsepsi gajah sebagai makhluk yang paling mengerti hutan, sama dengan apa yang dikatakan dalam Naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian, naskah Sunda kuno yang ditulis pada tahun 1518.
Di dalamnya ada ungkapan tentang sosok yang lebih tahu mengenai hutan: “Gajendra carita banem” (ingin tahu hutan, tanyalah gajah). Tentu saja naskah keagamaan itu tidak meminta manusia bertanya langsung kepada gajah, tetapi (mungkin) kepada manusia yang secara kapasitas diserupakan dengan gajah.
Dikutip dari situs Perpustakaan Nasional RI, dikabarkan, baru-baru ini, Dewan Eksekutif UNESCO menetapkan naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian dan Karya-karya Hamzah Fansuri masuk 74 nominasi register Memory of the World (MoW) periode 2024-2025 yang diusulkan oleh International Advisory Committee (IAC) MoW UNESCO dari total keseluruhan nominasi awal dari negara-negara anggota sejumlah 122 secara konsensus.
Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian diajukan oleh Perpusnas dalam register internasional MoW. Naskah ini hanya dimiliki oleh Indonesia dan saat ini disimpan di Perpusnas dengan nomor registrasi L 630. Sementara Karya-karya Hamzah Fansuri diajukan bersama (joint nomination) oleh Perpusnas dan Perpustakaan Negara Malaysia.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Naskah Siksa Kandang Karesian akan membawa pembacanya kepada pitutur (nasihat) tentang beragam hal yang cocok dituruti oleh ayah, ibu, anak, dan semua orang di dalam masyarakat untuk kemaslahatan fisik maupun spiritual.
Jika diterjemahkan, Siksa Kandang Karesian adalah “Ajaran Suci bagi Masyarakat dari Kalangan Resi”. Resi merupakan satu bagian dari Pola Tiga Sunda (Tritangtu). Yakni, Rama, Ratu, Resi. Ketiga lembaga ini berposisi sejajar. Resi adalah kaum agamawan.
Dikutip dari situs Perpustakaan Nasional, bahwa Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian dinilai memiliki signifikansi universal, karena di dalamnya terkandung ajaran moral masyarakat Sunda yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan integritas.
Selain itu, naskah ini juga sebagai artefak kebudayan, karena menggambarkan hubungan sosial, politik, dan ekonomi orang Sunda dengan bangsa lain pada abad ke-16.
“Naskah ini termasuk langka karena hanya ada dua naskah saja di dunia sehingga nilai signifikansinya sebagai dokumen, tidak tergantikan,” tulis situs Perpusnas RI.
Dua naskah yang dimaksud adalah ada di Perpusnas RI dengan nomor naskah L 630 dan L 624. Keduanya merupakan naskah Sunda Kuno tertua yang mencantumkan tahun penulisannya.
Sanghyang Siksa Kandang Karesian dengan nomor L 630 adalah naskah daun lontar yang didapatkan pelukis Raden Saleh ketika berkeliling di Priangan. Naskah bertanggal nora catur sagara wulan (0-4-4-1), yaitu tahun 1440 Saka atau 1518 Masehi.
Naskah lainnya, yaitu L 624 dalam peti kabinet nomor 69 didapatkan dari pemberian Bupati Bandung Wiranatakusumah IV (1846-1874) kepada BGKW (Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen), sebuah lembaga kebudayaan yang dulunya berlokasi di Batavia (Jakarta), sekitar paruh kedua abad ke-19.
Karena berbentuk puisi, naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian banyak mengandung kalimat yang cocok untuk dikutip. Jika dibunyikan, kutipan-kutipan itu menghasilan jalinan kata yang indah terdengar.
Di antaranya adalah kutipan yang banyak dijumpai dalam unggahan di media sosial ialah tentang sumber kesenangan menurut Sang Darma Pitutur yang mengandung seloka (perumpamaan):
Tadaga carita angsa
Gajendra carita banem,
Matsyanem carita sagarem
Puspanem carita bangbarem
(Bila ingin tahu telaga, tanyalah angsa
bila ingin tahu hutan, tanyalah gajah
bila ingin tahu laut, tanyalah ikan
bila ingin tahu bunga, tanyalah kumbang).
Di dalam naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian ini pula, ada cerita tentang penggunaan kujang. Senjata tajam asli Jawa Barat dengan lengkung yang khas itu, pada silam masa bukan diperlakukan sebagai pusaka, melainkan senjata yang digunakan oleh petani.
Sebaliknya, golok yang kini dipakai sebagai alat kebanyakan petani, dahulu kala merupakan senjata yang digunakan oleh raja. Di dalam naskah itu diterangkan ihwal jenis-jenis senjata.
“Senjatanya sang prabu adalah pedang, abet, pamuk, golok, peso, tondot, keris, raksaksa dijadikan dewanya, itulah senjata guna membunuh (musuh). Senjatanya petani adalah : kujang, baliung, patik, kored, sadap, Detya dijadikan dewanya; itulah untuk mengambil apa yang bisa dimakan dan diminum.” (Terjemahan Siksa Kandang Karesian, Depdikbud RI tahun 1992). naskah kuno