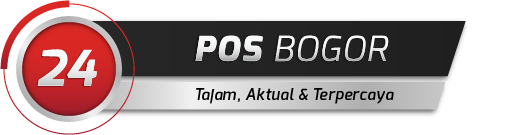Sunda sebagai wilayah dihuni oleh masyarakat yang punya upacara adat. Berbagai hal mulai dari menanam padi, memanen, hingga pernikahan ada upacara adatnya. Upacara adat itu bahkan ada yang masih dilestarikan hingga kini.
Upacara adat jika ditelusuri sumbernya, memang tidak ada sumber pasti sejak kapan upacara itu dilakukan oleh para leluhur orang Sunda, namun yang jelas upacara adat diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini.
Saat ini, sebagian masyarakat yang di perkotaan cenderung untuk tidak melaksanakan upacara adat. Boleh jadi selain karena pelaku upacara adatnya sudah berkurang karena usia, biaya untuk membeli perlengkapan upacara juga terbilang mahal dengan barang-barang yang juga langka. Namun, di pedesaan, upacara adat masih dipegang teguh. Upacara adat Sunda penuh dengan simbol-simbol pengajaran tentang kebaikan.
Dalam artikel ini, akan dibahas setidaknya 10 upacara adat yang masih dilestarikan hingga kini oleh sebagian masyarakat kota dan desa di Sunda.
Upacara adat Mitembeyan adalah upacara adat Sunda yang dilakukan sebelum memulai menanam padi. Secara harfiah, ‘mitembeyan’ bermakna memulai. Biasanya, mitembeyan dilakukan dengan membuat sesajen. Upacara ini dipimpin oleh tetua kampung atau lebe (penghulu).
Tujuan dari upacara ini adalah untuk meminta izin dan berkah kepada Tuhan sebelum melakukan pekerjaan yang akan dimulai, yakni menanam padi. Mitembeyan sendiri sejatinya dimulai saat padi di penyemaian sudah siap ditebar dan ditanam di lahan sawah.
Nanti di tengah-tengah, ketika padi mulai berbulir, orang Sunda pemilih sawah akan memperlakukan hamparan pagi itu selayaknya perempuan yang sedang mengandung, jadi betul-betul dirawat dengan baik. Di sini pun ada upacara lagi yang isinya berdoa untuk kemulusan padi hingga panen.
Jika padi telah ranum, sudah saatnya ia dipanen. Orang Sunda pantang memetik bulir padi atau buah pada pohon tanpa meminta izin. Orang Sunda terikat ungkapan ‘mipit kudu amit, ngala kudu menta’ (memetik harus pamit, menuai harus meminta).
Maka, ada upacara nyalin. Upacara adat Nyalin adalah upacara untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dan mulai memanen padi yang dianugerahkan itu. Selain itu, nyalin berarti menyiapkan kembali sawah yang telah dipanen untuk ditanami kembali.
Dalam Wawacan Sulanjana, disebutkan bahwa padi di Sunda ada karena perantaraan Nyi Pohaci atau Dewi Sri. Maka, tak pelak Nyi Pohaci juga termasuk tujuan yang kepadanya disampaikan terima kasih.
Hasil panen yang melimpah sudah sepatutnya disyukuri. Masyarakat Sunda bersyukur atas hasil panen selama setahun dalam bentuk upacara adat Seren Taun.
Secara harfiah ‘seren’ berarti menyerahkan, semantara ‘taun’ adalah tahun. Jadi, Seren Tahun bisa dimaknai sebagai ‘serah terima atau pergantian tahun, dari tahun sebelumnya ke tahun yang baru’.
Seren taun biasanya diisi dengan aktivitas menyerahkan hasil panen ke dalam leuit atau lumbung padi. Di Sunda, leuit atau lumbung padi tidak dikuasai oleh perorangan, melainkan milik adat untuk kemaslahatan penduduk. Lokasinya juga terpisah dari pemukiman. Ini dilakukan untuk menjaga jika terjadi peristiwa bencana misalnya kebakaran. Jika kampung terbakar, leuit sebagai cadangan pangan tetap aman.
Ungkapan rasa syukur nyatanya bukan hanya bisa dibunyikan dengan kata-kata seperti dalam doa. Masyarakat juga bisa bersyukur dengan musik dan kudapan.
Di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dikenal upacara adat Ngalaksa. Upacara ini dilakukan setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen padi dan sebagai penghormatan terhadap Nyi Pohaci.
Dalam upacara ini dimainkan kesenian tradisional Tarawangsa. Orang-orang hanyut dalam petikan jentreng dan bunyi tarawangsa. Mereka bisa menari mengikuti irama musik yang ‘mistis’ itu dengan selendang terkalung di leher.
Selain itu, Ngalaksa juga diisi dengan prosesi membawa padi ke lumbung, membuat makanan laksa (sejenis makanan dari tepung beras), dan berbagai kegiatan ritual lainnya.
Drama dalam bahasa Sunda berjudul “Amat Jaga” karya Saini K.M. yang dipentaskan Teater Awal Bandung menampilkan adegan ketika Amat yang hasil panennya melimpah mengajak perempuan bernama Tiwi untuk menikah.
Hasil panen melimpah membuat seorang lelaki di Sunda mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun, sebelum menikah, ada upacara adat ‘Ngeuyeuk Seureuh’ yang harus dilalui.
Upacara ini semacam ‘pendidikan seks’ untuk calon pengantin. Upacara ‘ngeuyeuk seureuh’ atau ‘mengolah sirih’ bagi laki-laki dalam tradisi Sunda merupakan bagian dari upacara pernikahan adat yang memiliki makna mendalam.
Di dalam upacara itu bukan sebatas pendidikan seks, namun nyatanya ada pedoman kehidupan rumah tangga. Dalam ‘ngeuyeuk seureuh’, calon pengantin laki-laki membelah bunga pinang (simbol perempuan) dan menyiapkan sirih yang akan digunakan dalam ritual.
Dalam tradisi pernikahan di Sunda, ada upacara sawer. Sawer yakni seorang juru kawih atau juru sawer mendendangkan lagu sawer yang isinya penuh dengan nasihat agar kedua mempelai mendengarkan dan diharapkan mengikuti nasihat-nasihat di dalam bahasa Sunda itu.
Pada akhir nasihat, sering dibubuhi dengan aksi menebarkan uang koin yang menjadi rebutan hadirin pesta pernikahan yang notabene merupakan para pengantar pengantin (peserta seserahan) dan tuan rumah.
Di antara hikmah pernikahan adalah lahirnya generasi baru. Perempuan mengandung dan melahirkan. Namun di Sunda, kehamilan adalah sesuatu yang sangat dijaga sehingga perlu doa-doa keselamatan untuk sang ibu dan janin. Maka, ada upacara adat Tingkeban.
Tradisi ini punya kemiripan dengan tradisi di etnis Jawa. Di Sunda, tingkeban merupakan upacara adat yang dilaksanakan ketika perempuan menginjak usia hamil 7 bulan. Biasanya, dilakukan sejumlah ritual seperti mandi air kembang.
Selebihnya, syukuran dengan cara berdoa, berbagi makanan, bahkan ada yang berbagi rujak namun harus dibeli oleh anak-anak dengan benda berupa bentuk koin dari potongan genting.
Anak yang lahir di Sunda tak luput dari upacara adat. Anak-anak yang baru lahir biasanya menghadapi upacara ‘nenjrag bumi’ yang berarti menginjak atau menghentak bumi. Nenjrag bumi adalah sebuah upacara adat Sunda yang dilakukan saat bayi lahir yakni dengan memukulkan alu (alat untuk mengulek) ke tanah sebanyak tujuh kali. Ritual ini bertujuan agar bayi kelak menjadi berani, tidak mudah takut, dan terkejut.
Di dalam kamus, ngaruwat ditulis tanpa ‘w’, ngaruat. Artinya mengadakan doa-doa untuk menolak bala atau bencana. Orang yang baru punya rumah, misalnya, biasa mengadakan upacara ngaruat imah. Orang punya kendaraan baru, ngaruat kandaraan. Dan seterusnya.
Namun, ada istilah khusus yang dipakai sebagai upacara dari rangkaian upacara menghormati padi, yaitu Ngaruwat Bumi.
Dikutip dari situs Pemerintah Kabupaten Subang. Misalnya di Subang, Jawa Barat, upacara ngaruwat bumi telah berumur ratusan tahun. Namun kesakralannya sebagai tradisi masyarakat agraris tetap terasa.
“Ngaruwat bumi adalah ungkapan syukur atas hasil yang diperoleh dari bumi. Pengharapan setahun ke depan, serta penghormatan kepada leluhur. Ruat dalam bahasa sunda artinya mengumpulkan dan merawat. Yang dikumpulkan dan dirawat adalah masyarakat dan hasil buminya.”
“Ruwatan bumi juga disebut hajat bumi, menggenapi rangkaian upacara yang digelar sebelumnya, seperti: upacara hajat solok, Mapag Cai, mitembiyan, netepkeun, nganyarkeun, hajat wawar, ngabangsar, dan kariaan. Mayoritas diantaranya terkait proses pertanian, khususnya budidaya padi. Dengan tradisi ruwatan bumi, padi memiliki tempat istimewa. Padi atau beras, dalam keyakinan masyarakat setempat, tidak hanya sebagai bahan pangan. Padi diyakini bermula dari aktivitas dewi-dewi sehingga bersifat sakral dan segala proses menghasilkannya dipandang suci.” tulis situs itu.
Orang meninggal dunia di Sunda dikuburkan. Pada masa lalu dalam kisah-kisah berlatar zaman Pajajaran seperti dalam ‘Raden Banyak Sumba’ karya Saini K.M. jenazah orang Sunda dibakar dan abunya disimpan di tempat khusus.
Di Sunda masa kini, setelah menguburkan orang, para pengantar jenazah tidak langsung pulang, melainkan berkumpul dahulu di rumah duka. Tuan rumah akan mengadakan upacara adat Susur Tanah.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Susur tanah itu seperti acara tahlil atau kenduri kecil-kecilan yang dihadiri keluarga inti dan para pengantar jenazah. Di dalamnya diucapkan doa-doa yang baik, doa keselamatan agar ruh sang jenazah diterima amal baiknya dan diampuni kesalahannya.